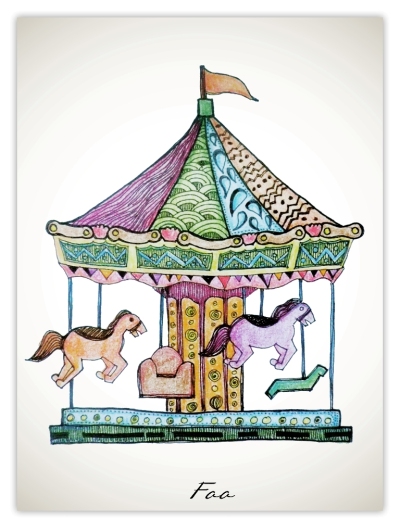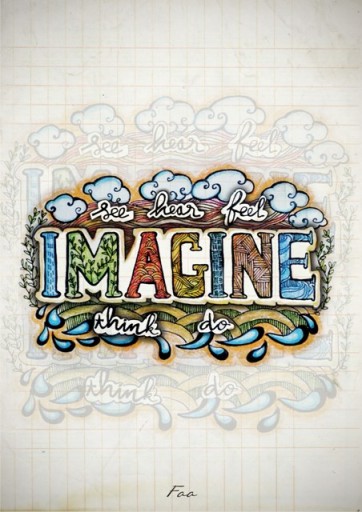Posted in coratcoret | Tagged hati, photostory, pintu, pulang | 2 Comments »
Anggap saja impian-impian seperti krupuk. Masukkan ke dalam kaleng, agar tetap renyah. Suatu saat bukalah, dan nikmati hasilnya.
Bagai makan tanpa krupuk, berasa ada yang kurang. Seperti juga hidup tanpa impian. Garing.
Posted in coratcoret | Tagged doodling, dream, hope & happiness, kaleng, krupuk, sket | 6 Comments »
Posted in bolangbelong | Tagged berjalan bergerak, lost, photostory, V | Leave a Comment »
Ada yang berjalan cepat-cepat. Diburu waktu, katanya. Ada yang harus cepat-cepat. Tak ingin tertinggal katanya. Tapi cobalah untuk berhenti sejenak. Biarkan detak jantung bekerja selayaknya. Tidak digesa-gesa. Duduklah, dan nikmati.
Posted in coratcoret | Tagged duduk, kursi, photostory | 2 Comments »
“Kamu beneran mau naik ini?”, salah satu teman yang saya pamiti bertanya sambil menunjuk motor saya. Setengah tidak yakin.
Ekspresi yang sudah saya duga, mengingat motor saya adalah motor tua. Motor pitung (C70) yang sudah dimodifikasi dari Honda Astrea Star tahun 1997. Motor kesayangan yang butuh proses lama untuk memilikinya. Saya namai Misel. Keren kan? Namanya doang maksudnya.
Entah setan dari mana yang membisikkan keinginan tidak wajar ini. Saya pengen touring ke suatu tempat naik pitung, dan pesertanya hanya perempuan. Partner in crime sesama sinting yang berhasil saya gaet adalah Indah. Saya dan Indah sama-sama pecinta motor pitung. Sekedar informasi, kelakuannya tidak seindah namanya.
Beberapa hari sebelumnya, Indah menawarkan ke Cilacap. Saya setuju. Mulai cari tahu rute perjalanan dan tempat-tempat yang akan dituju. Siap tancap gas. Maka dimulailah misi gorong-gorong ini. Hanya beberapa teman yang diberitahu kalau kami akan touring berdua saja. Naik motor sendiri-sendiri. Kami sudah berencana tidak akan memberitahu sebelum sampai Cilacap. Lebih tepatnya antisipasi malu jika misi gagal.
Menurut informasi, jarak Jogja-Cilacap bisa ditempuh 4-6 jam. Cukup panjang. Tapi tak apa. Biar santai asal sampai. Jam 8 malam kami mulai berpacu dengan kuda besi. Menembus jalanan beriringan dengan mobil, truk, bahkan tronton.
2 jam berkendara, tubuh kami sudah mulai meronta. Ambil sein kiri, kami menepi di pom bensin Purworejo, sekalian isi premium. Di sinilah bumbu perjalanan mulai terracik. Saat helm dan slayer kami lepas, ketahuanlah kalau dua makhluk betina. Maka diberondonglah kami dengan berbagai pertanyaan oleh petugas pom bensin. Kira-kira daftar pertanyaan yang berhasil kami himpun adalah:
“Mau kemana?”, “Dari mana?”, “Naik motor ini?”, Dan sebagainya… dan sebagainya. Namun ternyata di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut, para petugas pom bensin ini berbaik hati menawari tempat istirahat di mushola. Karena sebentar lagi pom tutup.
Saat kami duduk-duduk, tiba-tiba saja ada sebuah mobil mendekat. Wajar, karena kami istirahat di dekat toilet. Benar saja, satu per satu penghuni mobil keluar menuju kamar mandi. Seorang bapak mendekati kami. Pertanyaan yang sama dengan para petugas pom bensin kembali terlontar. Hanya saja kali ini lebih banyak dan mendetail. Sampai-sampai hampir seluruh penghuni mobil keluar karena melihat dua motor tua dengan dua makhluk cantik di sampingnya. Malam-malam pula. Untung bukan hantu. Salah seorang ibu sempat mencoba menaiki motor kami. Bahkan semakin getol menanyai kami.
“Kalian gak takut apa kalo tiba-tiba mogok di jalan?”, tanya si ibu.
“Kalo mogok ya nasib”, jawab Indah sambil senyum.
“Dasar, kalian ini cewek-cewek badung”, ledek si ibu.
Sejujurnya ada rasa takut itu wajar. Tapi kami harus berani. Berani itu kan bukan berarti tidak adanya rasa takut. Tapi tahu caranya menyikapi rasa takut. Juga tak lupa dukungan doa.
“Kami duluan ya”, salah satu dari mereka berpamitan.
Rupanya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Gombong. Bapak yang menyupiri kembali keluar, mendekati kami.
“Ini buat bekal perjalanan, hati-hati di jalan ya”, kata beliau sambil memberikan empat gelas air mineral.
Saya dan Indah bengong sesaat. Tampang kami memang tampang orang yang layak dikasihani. Terimakasih, hanya itu yang bisa kami ucap. Semoga Tuhan memberkati.
Perjalanan kami lanjutkan. Masih setia menembus jalanan dan dingin malam. Menikmati setiap guliran roda. Sayangnya kenikmatan kami sempat terganggu. Ketika sampai di Karanganyar, tiba-tiba seseorang dengan mengendarai RX King “mbleyer-mbleyer” dan mendekati arah kami. Kami maju, dia ngepot-ngepot di depan kami. Entah apa motivasi orang ini. Membuat saya semakin (maaf) tidak suka dengan pengendara RX King. Arogan di jalanan.
Akhirnya kami berhenti di depan rumah makan yang cukup ramai. Sembari menunggu pengendara RX King yang tidak jelas itu benar-benar pergi. Memangnya jalanan punya mbahmu apa?
Papan di pinggir jalan menunjukkan bahwa sudah sampai di Banyumas. Jam 12 malam lewat. Sudah waktunya tubuh dan mesin motor istirahat. Kami mendarat lagi di pom bensin. Tidur.
Setengah 5 pagi, Indah masih tidur. Langit juga masih gelap. Saya sudah tidak bisa tidur lagi. Mencoba jalan-jalan di dekat pom bensin, sembari menanti semburat pagi. Saya bertanya kepada pak satpam, berapa lama waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke Cilacap. 1-2 jam lagi, kata beliau. Ya.. senjata utama untuk sampai tujuan hanya bertanya. Tak ada GPS, telepon genggam saja buluk, lebih pantas untuk nimpuk anjing. Tapi tak apa, terkadang teknologi malah membuat diri malas berinteraksi.
Hampir 2 jam berkendara mencari-cari Teluk Penyu, sebagai tujuan pertama. Pintu masuk semakin jelas terlihat. Semakin jelas. Semakin jelas. Wow.. kami sudah berada di Pantai Teluk Penyu. Mencari-cari spot yang yahud, di dermaga. Sepi, hanya ada beberapa nelayan yang memancing ikan. Finally, Cilacap… \m/
Panas mulai menyengat, siap-siap pindah halauan. Benteng Pendem tujuan berikutnya. Tak jauh dari Teluk Penyu. Reaksi yang sama kembali terulang saat sampai di parkiran Benteng Pendem. Kira-kira seperti ini, “ini kenapa kok ada cewek-cewek cantik naik motor tua sampai sini. Plat AB dan H pula. Konslet otaknya apa gimana”.
Benteng Pendem adalah benteng pertahanan yang dibangun Belanda pada tahun 1861-1879 untuk mempertahankan wilayah jajahannya. Terdapat beberapa ruang. Di bagian atasnya ditanami tumbuh-tumbuhan agar tidak terlihat seperti benteng pertahanan. Masih terkesan spooky karena lembab dan gelap dalamnya.
Cukup lama kami berada di Benteng Pendem. Santai-santai di taman sampai tak terasa sudah jam 12 siang lewat. Lapar luar binasa. Eh.. tapi.. tapi.. kami belum mandi. Mampir di toilet, mandi dulu, biar makin kece.
Kembali di parkiran. Kami malah jadi ngobrol-ngobrol sama mas-mas tukang parkir. Namanya Mas Arif dan Mas Ageng. Lumayan, modal sepik-sepik dapat teman baru.
Lapar, kami pengen makan seafood. Rencananya kami pengen beli sendiri. Tapi setelah dikasihtahu sama Mas Arif kalau wisatawan yang beli pasti dikasih harga yang mencekik leher. Keeekkkkk…. Oke, kami makmum saja. Indah dan Mas Arif pergi membeli ikan, saya menunggu sambil ngobrol dengan tukang parkir yang lain dan penjual makanan, juga Aka, anaknya penjaga loket yang masih berumur 12 bulan. Ya.. kita harus baik-baik di wilayah orang.
Tak sampai 1 jam, 4 ikan bakar sudah dibawakan Mas Arif. Sebesar kepalan tangan, penuh daging pula. Melihatnya saja bikin ngiler, semi seret. Seret karena memikir nominal harga yang harus kami bayar.
“Ini harganya berapa, mas?”, tanya saya.
“Udah, makan aja”, kata Mas Arif.
Jawaban “makan aja” sama artinya dengan kami ditraktir. Ya.. DITRAKTIR. Padahal kalau membeli, harganya bisa 50ribu per ekor, itu kata bapak nelayan yang makan bareng kami. Lagi, kami dipertemukan dengan orang baik. Thanks God.
“Kalian jadi nyebrang ke Nusakambangan? Buruan ntar keburu sore”, tanya Mas Arif.
Tujuan kami selanjutnya adalah Pulau Nusakambangan. Dengan membayar 15ribu, sebagai sewa perahu. Saat itu terisi 5 orang termasuk saya dan Indah. Terlibat perbincangan lagi dengan 3 orang laki-laki yang ternyata 2 diantaranya juga orang Jogja. Hanya mengobrol sebentar saja kami sudah mulai akrab. Lebih tepatnya saya dan Indah yang sok akrab. Nama mereka Mas Rori, Mas Budi, dan mas yang satu lagi lupa namanya. -___-”
15 menit menaiki perahu, kami telah sampai di Pulau Nusakambangan. Saya dan Indah berjalan ke Pantai Karang Bolong. Di sini juga masih terdapat benteng pertahanan.
Pantai, pasir putih, dan karang-karang menjamu kami, tak banyak pengunjung. Huaahhh… holideiiii.. holideii.. ini baru namanya menikmati hidup.
“Ndah, kok kita bisa-bisanya sampai sini ya”, pertanyaan konyol spontan terlontar ketika gelangsuran di pasir.
“Karena kita sukar waras”, jawab Indah. Ya.. jawaban yang tepat.
Sudah mulai sore. Kami harus bergabung lagi dengan mas-mas tadi. Rupanya mereka di pantai sebelah. Kami ngobrol-ngobrol lagi dengan mereka. Reaksi yang sama ketika mengetahui bahwa kami berdua naik motor pitung dari Jogja – Cilacap.
“Kalian pasti lagi stres, ya?”, tanya Mas Budi.
Dan saya kasih tahu, ternyata Mas Rori adalah KAKAK KELAS SAYA WAKTU SD. Ngoookkkk..
“Tadi, sebelum ketemu kalian, dunia ini serasa luas. Tapi setelah ketemu kalian, dunia terasa sempit”, kata Mas Rori. Ngakak maksimal.
Jam 5 lewat, kami sudah kembali lagi ke parkiran Benteng Pendem. Hari sudah muali gelap. Kami berpisah dengan rombongan Mas Rori. Rupanya Mas Arif dan Mas Ageng masih setia menunggu kami.
Sudah terdengar suara adzan. Indah harus sholat. Diantarlah kami ke mushola dekat rumah Mas Arif. Baru kami tahu, ternyata Mas Arif dan Mas Ageng kakak beradik. Bahkan Mas Ageng punya kembaran, namanya Mas Agung. Rumah di sini berjarak sempit. Padat penduduk, tapi ramah-ramah.
Kami menyempatkan mampir ke rumahnya Mas Arif. Keluarganya menyambut hangat kedatangan kami. Ngobrol-ngorbol berteman es jeruk yang terhidang di meja. Benar-benar penyeka dahaga.
Tiba-tiba saja teras rumah Mas Arif sudah penuh dengan orang. Suerr… saya dan Indah berasa seleb. Kami tidak menyangka sambutan mereka sampai seheboh ini. Motor kami dilihat-lihat. Motor yang sebelumnya terparkir sembarangan, tiba-tiba saja sudah manis di depan teras. Kami speecless. Tujuan awal hanya main, justru malah dapat saudara baru.
Bapaknya Mas Arif menawari agar kami menginap saja di rumahnya. Tapi kami menolak, karena harus pulang. Indah masih harus melanjutkan pulang ke Salatiga. Malam itu kami meninggalkan rumah Mas Arif dengan perasaan yang serba tak terduga. Hanya bisa mengucapkan terimakasih dan jabat tangan. Juga bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang baik.
Kami berpacu lagi dengan kuda besi, meninggalkan Cilacap. Sampai di Banyumas, mata saya sudah tidak kuat. Sudah harus istirahat.
Paginya kami kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kami memilih jalur Daendles, atau jalur selatan. Udara masih segar, pemandangannya juga bagus. Ladang-ladang berhias garis pantai. Saat melewati sebuah jembatan, terlihat muara tempuran sungai dengan laut.
Saya berada di depan, menunjuk-nunjuk arah selatan. Pantai… pantai. Indah setali tiga uang dengan saya. Kami mendamparkan diri di Pantai Keburuhan, Purworejo.
“Ini kenapa lagi kita bisa sampai di sini, ya Ndah?”, pertanyaan konyol kembali keluar.
“Karena kita sukar waras”, sebagai jawaban pamungkas.
Posted in bolangbelong | Tagged Benteng Pendem, berjalan bergerak, Cilacap, Honda C70, Nusakambangan, Pitung | 12 Comments »
Kereta hampir berangkat. 3 menit lagi. Seperti yang sudah-sudah, saya sering hampir ketinggalan kereta. Entah karena terlalu antusias atau sifat nyantai yang sudah kelewat ngadat. Ya.. lumayan. Pacuan adrenalin berbuah kucuran keringat.
Saya, Ika, dan Pak’e Yula berangkat dari Jogja ke Lampung naik kereta jurusan Jakarta, diteruskan naik bus ke Merak lalu nyebrang ke Bakauheni, Lampung. Kami bisa saja memilih naik bus yang langsung ke Lampung. Tinggal duduk tenang, tanpa harus ganti-ganti jalur. Tapi bukan itu yang kami pilih. Selain persoalan kantong, saya hanya berfikir bukan rasa nyaman saat bepergian yang saya cari. Tapi cerita apa yang akan saya dapat ketika di perjalanan.
Berawal dengan menaiki ular besi yang membawa ratusan manusia, lalu berganti jalanan beraspal yang kami rasakan dari dalam bus. Beralih kapal ferry untuk mengarungi Selat Sunda. Hampir 3 jam terombang-ambing di tengah luasnya lautan. Menunjukkan betapa besarnya semesta. Dan betapa kecilnya saya sebagai manusia.
Kapal ferry menepi di Bakauheni. Berganti lagi angkutan darat. Bus. Selamat datang di tanah Andalas. Setidaknya itu yang saya rasakan ketika melewati jalan bypass Sukarno – Hatta. Jalan darat yang lebih pantas disebut sungai kering. Lebih dari 24 jam, total perjalanan kami. Waktu yang dilalui untuk sampai di rumah Mas Paeng, kawan yang siap direpoti selama beberapa hari.
Pulau Tegal, itulah tujuan kami. Seberang Pantai Ringgung, Pesawaran. 15 menit menyeberang pakai kapal nelayan. Jika kalian searching dengan keyword “Pulau Tegal”, ditemukanlah pulau indah begitu pun pemandangan bawah lautnya. Potongan surga untuk menyelam. Sayangnya bukan itu yang akan kami lakukan. Ada sisi lain yang perlu saya, begitu pun kalian tahu.
Sisi barat Pulau Tegal, itu tujuan utama kami. Ketika sampai, terlihat anak-anak berkumpul di sebuah gardu di pinggir pantai. 2 buah ayunan menjuntai dari dahan pohon jambu. Beberapa anak sedang duduk di atasnya. Rupanya mereka sudah menunggu kedatangan kami. Terutama Ika dan Mas Paeng yang memang sudah sering kesini. Mereka belum pernah bertemu saya dan Pak’e Yula, tapi sambutan mereka tak seperti baru bertemu orang yang belum kenal. Hangat dan ceria.
Hari itu hari Sabtu, hari juga masih siang. Jangan tanya kenapa mereka berkeliaran dan tak sekolah. Berdasar perbincangan saya dan Ika sebelum berangkat, di sini hanya ada seorang guru. Itu pun tidak setiap hari mengajar. Ya maklum saja, hanya digaji 30 ribu per bulan. Sekolahnya pun hanya terdiri dari satu ruang kelas yang dipakai dari kelas 1 sampai 3. Ada juga yang belum bisa baca tulis. Itulah kenyataan, di kota orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah paling elite. Sementara di sini mencari pengajar saja sulit.
Anak-anak di sini mayoritas anak nelayan berdarah Sunda. Jika sudah agak besar, ikut orang tuanya membantu melaut. Namun keingintahuan dan semangat belajar mereka sangat tinggi. Terlihat saat membaca buku-buku yang sengaja kami berikan pada mereka.
Selama beberapa hari banyak hal yang kami lakukan. Ika mengajari baca tulis, saya mengajak mereka menggambar dan mewarnai. Setidaknya itu yang baru bisa saya lakukan. Daya imajinasi mereka tinggi. Tanpa diajari teori warna, mereka sudah bisa memadupadankan warna. Menyenangkan. Bukankah suatu hal yang lebih baru berguna ketika dibagi?
Hal yang tak lupa kami lakukan adalah bermain. Misalnya memancing dan membakar ikan setiap pagi, juga ikut menemani Sahri dan Riki mencari pakan ternak sambil menyusuri pantai. Mereka menyebutnya “ngramban”. Belum juga rasa capek hilang, Wahyudi mengajak kami bermain ke rumahnya. Padahal rumahnya di balik pulau. Tepatnya di Teluk Pengantin. Sekitar 30 menit jalan kaki, menyusuri hutan. Rasanya benar-benar seperti kembali ke masa kecil. Bermain menyusuri pohon, memetik buah-buahan, lalu memakannya bersama-sama anak-anak.
Ibu, nenek dan adik Wahyudi menjamu kedatangan kami dengan bercerita banyak hal. Mulai dari kehidupannya sehari-hari, juga saat-saat dimana ibu Wahyudi pernah digigit ular kobra saat menyusuri hutan.
“Mbak, aku punya ikan krapu besar, fotoin ya..”, pinta Wahyudi memecah perbincangan kami.
Dengan bangga ia menunjukkan seekor ikan krapu hasil tangkapan ayahnya. Siapa yang menyangka, di balik keceriaan Wahyudi, ternyata ia mengidap penyakit di dekat alat kelaminnya. Harus dioperasi, kata orangtuanya. Sehingga ia belum bisa disunat. Sementara teman-teman sebayanya sudah.
Hari mulai gelap, kami harus kembali ke gardu. Anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Seperti biasa, setiap maghrib mereka mengaji di mushola. Di tengah keheningan pulau tanpa ada listrik terdengar lantunan ayat-ayat suci dari suara anak-anak saat mengaji, saya tiba-tiba teringat ibu. Hampir tiap dini hari ibu saya membaca Al-Qur’an.
*(warga menggunakan jenset sebagai sember listrik, itu pun hanya 3-4 jam setiap malam, tergantung persediaan bahan bakar yang mereka miliki)
Selepas anak-anak mengaji, di gardu kami berkumpul kembali. Mas Paeng datang dengan membawa martabak manis, menjadi bumbu malam itu yang terasa semakin manis. Meski malam hari, anak-anak laki-laki banyak yang bermain di kapal nelayan. Beberapa anak terlihat memancing.
“Kaki Aldi kena kail pancing”, teriak anak-anak.
Dengan dipapah teman-temannya, Aldi dibawa ke gardu. Kakinya terkena kail kancing milik nelayan ketika mereka bermain di kapal. Kail pancing yang cukup besar. Dengan isi cutter, dia berusaha menyayat kulitnya agar mata kail bisa terlepas. Melihatnya perasaan saya tidak karuan. Ika langsung mual juga pusing, berusaha menjauh tak ingin melihat.
Usaha Aldi tak berhasil, mata kail masih melekat. Air mata terlihat menetes, disertai isakan. Mas Paeng berusaha membuatnya tetap tenang. Ingin rasanya mengantarnya pulang ke rumah.
“Bapak ibu kamu lagi di rumah nggak?”, tanya saya.
“Bapakku udah meninggal”, jawabnya. Degggggg…. skak mat. Saya menyesal telah menanyakannya. Sepanjang dini hari hingga pagi kami tidur dalam keadaan tidak tenang.
Mati-matian kami merayu agar Aldi mau diajak ke Puskesmas. Padahal ibu Aldi tidak punya cukup uang untuk berobat. Sementara kapal Pak Nur sudah menunggu. Rayuan kami gagal. Hanya uang pemberian Mas Paeng berharap bisa sedikit membantu. Kami meninggalkan Pulau Tegal dengan lebih banyak diam.
Selepas dari Pulau Tegal, Pak’e Yula memutuskan pulang ke Jogja, saya ikut Ika ke rumahnya (masih di Lampung) untuk beberapa hari. Komunikasi selalu kami lakukan untuk mengetahui kabar anak-anak di Pulau Tegal, terutama Aldi. Baru 2 hari kemudian kail pancing di kakinya terlepas. Bahkan sudah bisa manjat pohon kelapa, katanya. Syukurlah. Saya dan Ika sudah bisa tenang.
Mental anak-anak di Pulau Tegal sekuat karang-karang yang selalu mereka lihat setiap hari. Keceriaan mereka secerah pendaran mentari ketika pagi. Semoga cita-cita mereka tetap tinggi, setinggi langit yang mereka tatapi. Semoga bisa kembali lagi untuk bermain dan berbagi.
Tak ada yang lebih manis saat itu selain menutup perjalanan pulang sembari menikmati senja di Selat Sunda, juga telepon dari ibu meski sekedar menanyakan kabar. Saya jawab dengan sedikit cerita, yang akan tersambung sesampainya di rumah.
Posted in bagibagi, bolangbelong | Tagged hope & happiness, Pulau Tegal | 13 Comments »
Posted in coratcoret | Tagged carousel, doodling, komedi putar, sket | Leave a Comment »
Beberapa hari ini saya sering memimpikan orang-orang yang pernah saya temui ketika mengunjungi suatu tempat atau melakukan perjalanan. Salah satunya Wahyudi. Dia adalah seorang anak yang berasal dari Pulau Tegal, Lampung.
Seorang anak berambut mendekati warna merah. Semir alam mampu mengubah warna asli rambutnya. Paparan sinar mataharilah yang menjadi semir itu. Tipikal khas anak pantai, badan berwarna coklat terbakar.
Di dalam mimpi, saya bertemu Wahyudi di acara motor. Lalu kami terlibat dalam suatu percakapan, yang intinya menanyakan kabar. Selebihnya saya lupa. Dia selalu menunjukkan mimik wajah ceria. Setidaknya bisa saya lihat dari caranya mengobrol yang selalu dibumbui dengan tawa.
Kami bertemu lagi lewat mimpi. Setelah Maret kemarin yang menjadi awal perkenalan kami. Saya sering mereka-reka apa arti dari mimpi yang saya alami. Mimpi, ruang imaji di luar batas sadar itu seakan-akan menjadi reminder. Upaya pengingat bahwa pernah mengalami suatu hal. Salah satunya saya pernah ke Pulau Tegal.
Seperti setingan auto, ingatan saya secara otomatis kembali ke satu bulan kemarin. Saat saya bertemu, bermain, berbagi dan belajar bersama anak-anak di Pulau Tegal, salah satunya Wahyudi.
Wahyudi telah mengingatkan. Mengintakan lewat mimpi. Bahwa banyak cerita saat berada diantara kalian. Cerita yang harus saya bagi.
Bersambung
Posted in bagibagi, bolangbelong | Tagged hope & happiness, Pulau Tegal, Wahyudi | 2 Comments »
Posted in coratcoret | Tagged book, doodling, sket | 1 Comment »
Tak ada televisi layar datar layaknya di tempat karaoke. Tak ada. Cukup laptop 11 inchi walaupun perlu memicingkan mata saat menatapnya. Tak apa, yang penting lirik lagunya masih terbaca.
Tak ada sound system dengan daya mega watt layaknya konser musisi idola. Tak ada. Cukup sound system ala kampung dengan daya seadanya. Tak apa, kami sudah serasa artis idola bersuara emas. Setidaknya idola bagi diri sendiri.
Tak ada grup Orkes Melayu ala dangdutan pantura. Tak ada. Cukup “Orkes Suwung”, komposisi gitar, tamborin, dan ketipung bentuk dadakan musisi kampung.
Tak ada penari-penari dengan kostum berwarna-warni. Tak ada, juga tak perlu. Kami bebas menari sampai tinggi tapi masih terkendali.
Tak ada daftar lagu beratus-ratus layaknya menghafal rumus. Tak ada. Cukup unduhan lagu dengan bantuan Google, juru selamat dunia maya. Saat tak hafal lirik lagunya, cukup ganti dengan “lalalalala”. Kalau kepepet bisa berhenti seenaknya, yang justru menghasilkan gelak tawa.
Tak ada aturan tangga nada layaknya kontes tarik suara. Tak ada. Shalawatan dan tembang Jawa pun bebas disuarakan oleh mereka yang lanjut usia. Karena ini Malam Karaoke Syalala.
Genjrengan gitar tak mengenal aturan paten. Abaikan aturan tangga nada. Nyanyikan saja sesuka hati. Semua bebas bersuara, tak mengenal batas usia. Dari lagu khas panggung rakyat macam dangdut, campur sari, hingga Iwan Fals, idola Orang Indonesia. Tak lupa pembangkit kenangan ala Ida Laila.
Pilihlah lagu kesukaan, lalu nyanyikan. Hingga tak kuasa menahan tarian. Bebaskan. Karena ini Malam Karaoke Syalala.
Jika yang sederhana saja mampu mengundang tawa bahagia, untuk apa bermewah-mewah? Karena berbagi tak selamanya berwujud materi.
#Malam Karaoke Syalala, 3 tahun Komunitas Canting bersama warga Ripungan, Prambanan.
16 Februari 2013
Posted in bagibagi, bolangbelong | Tagged hope & happiness, karaoke, Komunitas Canting, Ripungan, Studio Biru | 6 Comments »